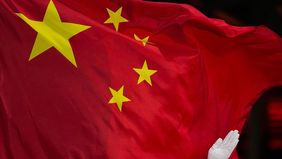Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan dan kebijakan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai merupakan ancaman serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Walau demikian, pemerintahan dan kebijakan Trump dianggap bukanlah bom waktu bagi perekonomian Indonesia.
"Secara gamblang bahwa dunia hari ini bukan lagi ruang isolatif yang bisa ditaklukkan dengan retorika kampanye semata. Dalam konteks ekonomi global yang saling terkait, ia mengingatkan bahwa kebijakan politik yang dibangun di atas janji kosong justru dapat menjadi benih kehancuran ekonomi jangka panjang," ujar R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Rabu, 9 April 2025.
Apa yang terjadi di AS, kata dia harus menjadi peringatan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemenangan Trump yang dibalut jargon nasionalisme ekonomi, justru melahirkan kebijakan tarif tinggi yang merusak ekosistem perdagangan internasional dan memicu gelombang inflasi global.
Apalagi, langkah Trump menaikkan tarif tinggi untuk seluruh impor, dan lebih tinggi lagi bagi negara dengan defisit perdagangan terhadap AS, Indonesia terkena imbas 32% tidak hanya menimbulkan distorsi pasar, tetapi juga mengoyak tatanan perdagangan multilateral yang selama ini menopang stabilitas ekonomi dunia. Haidar Alwi menyebut tindakan itu sebagai bentuk neo-merkantilisme destruktif yang memperlihatkan kekeliruan fundamental dalam memahami keterkaitan ekonomi antarnegara.
“Tarif tinggi memang melindungi industri tertentu dalam jangka pendek, tapi memukul daya beli, menaikkan ongkos produksi, dan menghantam petani serta manufaktur kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi domestik,” papar Haidar Alwi.
Menurutnya, ini merupakan contoh klasik dari paradoks perlindungan, di mana proteksi ekonomi justru memperlemah struktur ekonomi nasional dari dalam.
Salah satu istilah penting yang ia angkat adalah non-linear feedback loop, yakni situasi di mana dampak kebijakan tidak terjadi secara langsung dan proporsional, melainkan membentuk gelombang berulang yang semakin memperparah keadaan. Tarif tinggi memicu retaliasi, retaliasi memicu ketidakpastian, dan ketidakpastian menghancurkan kepercayaan investasi. Akibatnya, sektor riil stagnan, suku bunga tak bisa dikendalikan, dan konsumen akhirnya menjadi korban terakhir dari drama ekonomi yang dimainkan atas nama patriotisme palsu.
Menurut Haidar Alwi, Brexit adalah wajah lain dari kegagalan memahami dimensi ekonomi-politik secara utuh. Janji 'Take Back Control' dan klaim dana £350 juta per minggu untuk sistem kesehatan Inggris menjadi bukti bahwa narasi populis yang menyesatkan bisa menciptakan ilusi stabilitas.
“Inggris memang keluar dari Uni Eropa, tapi mereka kehilangan kendali dalam proses pengambilan keputusan regional. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari arsitek sistem, melainkan hanya menjadi pelaksana konsekuensi,” jelas Haidar Alwi.
Ia menilai, kampanye seperti ini berakar dari false equivalence, menggambarkan kompleksitas kebijakan dalam bentuk pilihan biner, seolah semua persoalan bisa diatasi dengan menarik diri dari interdependensi global.
Belajar dari kekeliruan Trump dan Brexit, Haidar Alwi menawarkan formula solusi konkret dan multidimensi bagi Indonesia agar tidak terseret dalam arus global yang membahayakan stabilitas jangka panjang.
Pertama, pemerintah harus memperkuat capacity for policy calibration, yakni kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi secara presisi berdasarkan dinamika domestik dan eksternal. Ini berarti penguatan data ekonomi real-time, konsolidasi lintas lembaga, dan pengembangan predictive economic modelling yang lebih akurat agar tidak terjebak dalam kebijakan populis.
Salah satu contoh nyata kebijakan populis yang perlu dikalibrasi ulang adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Prabowo Subianto dalam masa kampanye. Meski secara niat program ini tampak mulia, namun dalam praktiknya, program ini berpotensi menjadi beban fiskal yang luar biasa besar bagi anggaran negara. Proyeksi awal menyebutkan bahwa program ini akan menyedot lebih dari seratus triliun rupiah per tahun, sebuah angka yang dapat mengganggu postur APBN secara keseluruhan, apalagi jika tidak disertai dengan penguatan penerimaan negara.
Haidar Alwi berpandangan, kebijakan semacam ini harus diputuskan bukan berdasarkan sentimen elektoral semata, melainkan berdasarkan kajian kebutuhan dan kemampuan negara secara objektif. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, dengan ancaman fluktuasi harga pangan, energi, serta perlambatan ekspor-impor, program yang bersifat pengeluaran besar tanpa hasil jangka panjang yang terukur harus dikaji ulang secara rasional.
"Apabila negara memaksakan menjalankan program hanya karena janji politik, tanpa dasar kemampuan anggaran dan efisiensi manfaat, maka yang dikorbankan bukan hanya stabilitas fiskal, tapi juga kepercayaan investor dan kualitas belanja negara secara keseluruhan," kata Haidar Alwi.
Program makan bergizi gratis bisa ditunda pelaksanaannya, dialihkan menjadi proyek pilot di beberapa daerah tertentu untuk pengujian efektivitas, atau bahkan diganti dengan kebijakan penguatan gizi berbasis keluarga miskin secara terarah lewat program subsidi langsung pangan. Anggaran yang semula dialokasikan untuk membiayai program tersebut dapat dialihkan ke sektor yang lebih strategis, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, digitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, atau penguatan cadangan energi nasional yang saat ini jauh dari aman.
Dengan pendekatan policy recalibration ini, Indonesia tidak hanya akan menghindari jebakan populisme fiskal, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi—bahwa sebuah janji kampanye pun tetap harus tunduk pada prinsip akuntabilitas kebijakan dan kemampuan negara yang riil.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa kekuatan sebuah pemerintahan bukan terletak pada keberanian menepati janji, tapi pada kebijaksanaan menyesuaikannya dengan realitas—karena janji yang tidak relevan bisa berubah menjadi jebakan yang memukul balik rakyat itu sendiri.
Kedua, Indonesia harus memperdalam keterlibatan dalam ekonomi jejaring multipolar. Menurut Haidar Alwi, aliansi ekonomi seperti ASEAN, BRICS, dan Kemitraan Strategis Selatan bisa menjadi saluran diversifikasi pasar, penguatan teknologi, dan pengamanan rantai pasok. “Jangan bergantung pada satu pasar ekspor atau satu kekuatan besar. Tanam akar di banyak tanah,” tegasnya.
Ketiga, dibutuhkan pendekatan asymmetric economic diplomacy, yaitu strategi diplomasi ekonomi yang tidak mengandalkan kekuatan pasar semata, tapi memanfaatkan keunggulan struktural seperti stabilitas politik, bonus demografi, dan sumber daya alam strategis untuk menekan mitra dagang agar berlaku adil.
Keempat, Haidar Alwi menyarankan penguatan sistem pengawasan fiskal dan moneter yang bersifat antisipatif, bukan reaktif. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tanggap Ekonomi Global yang melibatkan ahli lintas sektor untuk memantau dan merespons gejolak ekonomi internasional secara cepat, terutama yang berdampak pada harga pangan, energi, dan komoditas utama.
Haidar Alwi mengingatkan, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas fondasi kejujuran politik dan akurasi ilmu pengetahuan. Dunia saat ini bergerak dalam lanskap adaptive complexity realitas di mana kebijakan tunggal bisa memiliki dampak berganda yang tidak terduga. Oleh karena itu, hanya pemimpin dengan visi sistemik dan pemahaman makro yang dalam yang bisa menavigasi Indonesia menuju kemandirian sejati dalam keterhubungan global.
 R. Haidar Alwi.
R. Haidar Alwi.
Dalam pandangan Haidar Alwi, masa depan Indonesia tidak bisa digantungkan pada satu kutub kekuatan global. Ia harus dirancang sebagai ekosistem mandiri yang mampu bertahan dalam badai geopolitik, namun tetap lentur dalam bersinergi. Karena kekuatan sejati bukan pada mereka yang memukul dunia, tapi pada mereka yang mampu menari bersamanya tanpa kehilangan arah.
Haidar Alwi menekankan bahwa janji kampanye dalam demokrasi bukanlah sekadar alat untuk meraih dukungan, melainkan kontrak kebijakan yang memiliki konsekuensi luas.
“Kita tidak bisa lagi menilai pemimpin dari betapa keras ia bersuara di panggung, tapi seberapa cermat ia mengukur efek dari setiap kata yang diucapkan,” pungkas Haidar Alwi.

 Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Antara/Anadolu/py)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Antara/Anadolu/py)