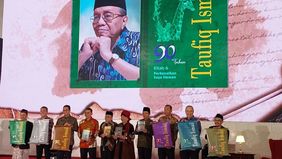Ntvnews.id, Jakarta - Masih hangat dalam ingatan betapa gegap gempitanya dunia sastra Indonesia ketika negara kita menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi Guest of Honor di Frankfurt Book Fair 2015. Kita membawa 70 penulis dan lebih dari seribu judul buku ke panggung literasi terbesar dan tertua di dunia. Satu dekade berlalu, di tengah ancaman merosotnya minat baca dan masifnya digitalisasi, muncul pertanyaan penting: masih relevankah buku dan sastra hari ini? Di balik keraguan itu, keberhasilan sastrawan kita dalam menembus forum internasional maupun pasar domestik membuktikan bahwa talenta sastra Indonesia tetap bernapas kuat.
Tahun 2016, novel Man Tiger karya Eka Kurniawan masuk longlist International Booker Prize—pencapaian perdana bagi sastrawan Indonesia. Satu tahun sebelumnya, novel Beauty is a Wound-nya masuk dalam daftar 100 buku paling penting versi The New York Times. Di Tanah Air, sastrawan kita telah lebih dahulu menjadi tuan rumah di dunia perbukuan nasional. Buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, misalnya, telah mencapai cetakan ke-95. Karya penulis produktif seperti Dewi Lestari, Ika Natassa, Tere Liye, hingga J.S. Khairen terus meramaikan rak-rak best-seller. Bahkan, banyak karya sastra Indonesia yang dialihwahanakan ke medium film dan serial. Dari Ayat-Ayat Cinta hingga Laskar Pelangi, dari Dilan hingga Gadis Kretek yang masuk daftar top 10 dunia di Netflix—semuanya menandakan bahwa karya sastra masih hidup dan terus berkembang lintas platform.
Namun di balik pencapaian tersebut, bayang-bayang penghidupan yang rapuh tetap menaungi banyak sastrawan. Honorarium yang diterima kerap tak sebanding dengan kedalaman batin dan waktu yang dicurahkan. Banyak penulis harus membagi hidup antara menulis dan pekerjaan lain demi menyambung hidup. Ruang penerbitan semakin sempit, media sastra terpinggirkan, dan penghargaan jarang memberi dampak ekonomi nyata. Akibatnya, krisis kesejahteraan tak terhindarkan.
Ancaman Krisis Regenerasi
 Pelaksanaan revitalisasi naskah kuno Lampung yang mulai rusak termakan zaman yang tersimpan di Museum Lampung oleh Perpustakaan Nasional. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)
Pelaksanaan revitalisasi naskah kuno Lampung yang mulai rusak termakan zaman yang tersimpan di Museum Lampung oleh Perpustakaan Nasional. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)
Perlu diketahui, krisis kesejahteraan sastrawan bukanlah sekadar masalah mikro individu, melainkan cermin kelemahan sistem budaya kita. Krisis regenerasi talenta sastra yang tak kunjung surut ditandai dengan menipisnya jumlah penulis baru dan pasar yang kian menyempit. Untuk menjawab persoalan ini dibutuhkan intervensi sistemik. Pemerintah, melalui Bappenas dan Kementerian Kebudayaan, menjalankan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya sebagai program strategis jangka panjang. MTN mengusung empat pilar: Pendataan Talenta melalui sistem informasi terpadu, Pembibitan lewat pelatihan, pendampingan, dan inkubasi, Pengembangan melalui residensi, masterclass, dan akses pasar, serta Internasionalisasi untuk membuka jalur distribusi dan rekognisi global.
MTN dirancang untuk menguatkan lima bidang utama seni budaya: Seni Pertunjukan, Musik, Film, Rupa, dan Sastra. Pijakan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Perpres ini menetapkan peta jalan MTN hingga 2045 dengan lima fase: Fondasi (2024), Penguatan (2025–2029), Pemantapan (2030–2034), Keberlanjutan (2035–2039), dan Puncak Pencapaian (2040–2045). Gugus Tugas MTN bernaung langsung di bawah Presiden yang diharapkan menjamin sinkronisasi lintas kementerian, daerah, dan pemangku kepentingan.
Jika seluruh tahapan ini dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, karier sastrawan dapat dibangun dari benih bakat hingga kematangan karier. Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) menjadi fondasi pendataan, mengklasifikasi penulis ke dalam kategori bibit, potensial, dan unggul. Langkah ini menghindarkan talenta muda dari keterpinggiran dan memastikan mereka terekam dan terlindungi. Dukungan jaminan sosial dan perlindungan HAKI menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjadikan sastra sebagai profesi yang layak.
MTN juga menjemput benih-benih kreativitas dari seluruh penjuru negeri—dari pelajar di kota besar hingga anak-anak di pelosok—melalui sesi diskusi inspiratif, pertunjukan sastra, lokakarya intensif, hingga pendampingan oleh para mentor dari komunitas dan kampus. Talenta potensial selanjutnya diberi ruang untuk menjalani residensi, masterclass, hingga proses inkubasi karya. Karya-karya tersebut dipresentasikan dalam forum-forum prestesius seperti Ubud Writers & Readers Festival dan Jakarta International Literary Festival, kemudian dikapitalisasi melalui ajang-ajang seperti Indonesia International Book Fair dan Jakarta Content Week.
Langkah ini diharapkan dapat mengubah royalti dari angka simbolik menjadi aliran penghidupan yang berkelanjutan. MTN juga mendorong pembentukan pasar internasional di Indonesia, sekaligus memfasilitasi mobilitas sastrawan ke ajang sastra global. Dengan roadmap yang jelas, sastrawan tidak lagi berlayar sendiri, melainkan didukung oleh diplomasi budaya yang strategis.
Rekomendasi Aksi Nyata
 Pelaksanaan revitalisasi naskah kuno Lampung yang mulai rusak termakan zaman yang tersimpan di Museum Lampung oleh Perpustakaan Nasional. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)
Pelaksanaan revitalisasi naskah kuno Lampung yang mulai rusak termakan zaman yang tersimpan di Museum Lampung oleh Perpustakaan Nasional. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)
Lalu, bagaimana agar MTN benar-benar menjawab krisis regenerasi ini? Setidaknya ada tiga lini aksi yang harus diperkuat. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengadopsi SIMT secara merata di seluruh provinsi. Ini penting agar data menjadi dasar kebijakan. Anggaran khusus perlu dialokasikan untuk beasiswa, residensi, dan festival sastra lokal. Kedua, industri kreatif dan penerbit perlu bermitra dengan MTN dalam mengembangkan program inkubasi penerbitan digital serta skema distribusi yang adil dan transparan. Mekanisme royalti berbasis keterlibatan pembaca juga harus segera diterapkan.
Ketiga, komunitas dan lembaga sastra perlu diperkuat sebagai pusat pembibitan. Mereka harus difasilitasi untuk menyelenggarakan pelatihan, membuka akses ke SIMT, dan menjalin kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan platform daring. Dengan sinergi antar-pemangku kepentingan, MTN dapat membangun ekosistem talenta sastra nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh,, MTN Seni Budaya dapat menjadi peta jalan yang konkret. Sastra Indonesia tidak akan terus “hidup di kertas kumal”, tetapi bersinar di panggung dunia. Profesi menulis akan menjadi pilihan yang bermartabat, dan generasi baru akan menyambung estafet budaya dengan keyakinan dan kebanggaan.
Penulis: Mohamad Atqa (Pamong Budaya Ahli Muda, Kementerian Kebudayaan RI)

 Mohamad Atqa, Pamong Budaya Ahli Muda, Kementerian Kebudayaan. (Dok. Kemenbud)
Mohamad Atqa, Pamong Budaya Ahli Muda, Kementerian Kebudayaan. (Dok. Kemenbud)